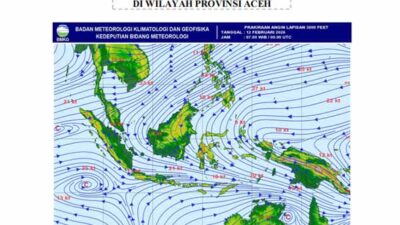Catatan: Iranda Novandi
Aroma busuk menyeruak saat kaki menjajaki diantara tumpukan sampah banjir dan genangan lumpur yang belum sempat mongering serta bangkai bus yang terongok tak bertuan…
SABTU 29 Desember 2025. Matahari mulai merapat ke peraduan di upuk barat. Pukul menunjukan sekitar pukul 18.00 wib. Saat saya dan teman-teman dari Persatuan Wartawa Indonesia (PWI) Aceh dan PT Wajib Usaha Mix (WU) memasuki jalan dua jalur di komplek Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.
Di sisi kiri jalan, terlihat satu unit mini bus jenis Damri terongok tinggal kerangka yang setengah bagian belakang tertimbun lumpur. Tidak jauh dari situ, puluhan tentara berseragam loreng TNI terlihat mulai merapatkan barisan untuk mendengar breafing komandan, tanda berakhirnya tugas hari itu dalam upaya pembersihan Kota Kuala Simpang dari sampah material lumpur banjir yang telah memporakporandakan kabupaten di ujung timur Aceh yang bebatasan langsung dengan Sumtera Utara (Sumut)
Di sisi kakan jalan, terlihat aktivitas tentara dan warga yang selama ini menetap di kamp pengungsian mulai mengambil langkah istirhat jelang magrib. Setelah seharian berjibaku dengan berbagai upaya percepatan pemulihan kondisi pascabencana.
Tak terasa bulir bening mulai mengantung di kelopak mata. Bukan cengeng. Ini cerita elegi, lebih 30 hari sudah bencana itu meninggalkan jejak. Meningkalkan banyak saksi bisu yang tak yang tak bisa berkata-kata. Kata-kata hanya milik pejabat di moncong media, sementara yang lain hanya bisa mengangguk, seakan mengangguk-anguk mendengarkan alunan musik yang happy di yang mainkan Disc Jockey (DJ) di klub malam di kota-kota besar.
Tak lama berselang, Erwan, Ketua PWI Aceh Tamiang, menghampiri rombongan PWI Aceh yang di komnadoi langsung Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin. Dengan sepeda motor yang penuh lumpur, Erwan mengarahkan sasaran utama ke posko pengungusian di Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Sebagian anak-anak terlihat bermain sebisa mereka, entah mereka suka atau tidak, namun itu harus mereka lakukan. Wajah-wajah duka terpancar jelas dari raut dan rona wajah-wajah polos situ.
“Dari mana Om,” tanya seorang ibu sambil mengendong bayi, Airin yang masih berumur 5 bulan.
Airin kecil yang baru Allah titipkan pada kedua orang tuanya dengan terpaksa harus merasakan penderitaan yang sangat dalam bersama orang tuanya tinggal di kamp pengungsian yang sudah selama sebulan.
Tidur dengan alas seadaanya hanya menutup lantai tanah di dalam tenda pengungsian. Merasakan dingin angin malam yang kapan saja bisa menyusup dari celah tenda, belum lagi rasa dingin tanah yang hanya bebatas selembar tikar yang dari para dermawan yang membantu mereka.
“Dari Banda Aceh,” jawabku lirih.
“Bawa bantuan ya untuk kami, dari lembaga apa Om,”
“Iya, kami dari PWI Aceh. ada bantuan dari masyarakat di Banda Aceh yang dikumpulkan untuk ibu-ibu dan adik-adik disni,” ujarku, sambil terus bertahan agar butir bening di kantong mata tak menetes.
“Kami sudah sebulan 2 hari dini Om. Entah sampai kapan,” ujar mama Airin lagi, sambil ditimplin ibu-ibu yang lainnya. “iya Om, sudah sebulan di sini,”
Aku tak mampu berkata-kata. Rasanya kalau hanya mengucapkan kata “sabar” bukan lagi satu hiburan bagi mereka. Karena sudah pasti kata-kata “sabar” sudah rastusan orang yang mengucapkannya, mulai dari presiden, para menteri, pejabat Negara, pejabat daerah dan para dermawan yang datang ke posko mereka.
“Kami pingin pulang ke kampong kami, tapi sudah tak ada apa-apa, semuanya sudah hilang lenyap di bawa banjir. Tapak rumah kamipun tak ada yang tersisa,” ujar ibu yang lain.
“InsyaAllah nanti pasti bisa pulang,” jawab ku menghibur, meski itu ku jamin tak akan menghibur hati mereka yang dilanda nelangsa yang mendalam.
Untuk keluar dari percakapan nan kaku, ku coba mencubit manja pipi Airin yang putih.
“Cantik kali ya, tembem lagi pipinya,” ujar ku
“Airin lagi sakit Om, pilek udah beberapa hari ini,” ujar ibundanya.
“Moga cepat sembuh dan bisa tersenyum lagi, biar makin cantik dan manis,” ujar ku.
“Ayo kita berfoto, mau?,” tanya ku seakan kehabisan bahan cerita.
“Maulah Om. Om aja yang foto kami,” ujar ibu-ibu yang lain yang tak sempat ku tanya nama mereka satu persatu.
“Oke, jawab ku. Mendengar kata ibu para ibu-ibu itu langsung memanggil para anak-anak mereka untuk ramai-ramai di foto. Dengan senyum yang dipaksa mereka tanpa ceria saat ku arahkan kamera handphone ku kearah mereka.
“Ibu-ibu sudah makan, kebetulan kami ada bawa banyak makanan, ada nasi, kuah belangong untuk ibu dan adik-adik sini,” ujar ku
“Apa tu kuah belonging,” tanya mereka
“kuah belongong itu, masakan khas Aceh Besar,”
“gak tau kami Om, gak pernah rasa,”
“Kuah belangon itu, kari daging atau kambing,” ujar ku sedikit menjelaskan
“Maulah mncobanya,” ujar ibu-ibu itu
“Entar lagi ya kita bagikan, setelah bapak-bapak itu selesai bicara,” ujar ku sambil menunjuk kea rah Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin yang sedang diskusi sistem pembagian dengan Katua DPRK Aceh Tamiang, Fadlon.
Tak lama berselang dari itu, akhirnya kuah belangonpun dibagikan. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka.[] bersambung “Nelangsa dari Kampung Banjir…”